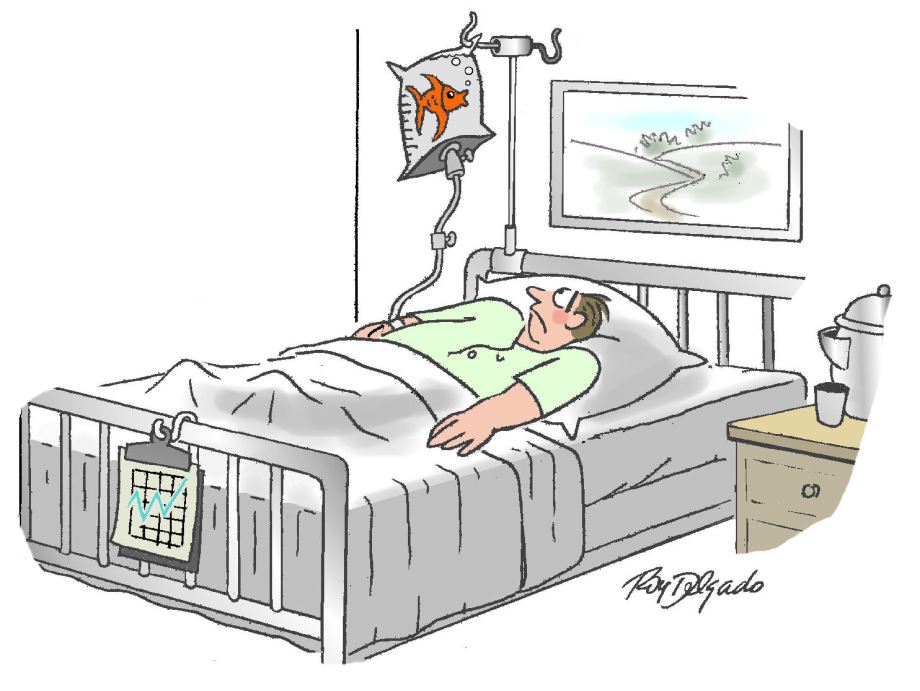https://www.instagram.com/p/BMcCql7geG9/?taken-by=fahrisalam
MENAMATKAN Sang Pengoceh, novel Vargas Llosa terjemahan Ronny Agustinus terbitan OAK. Merasa asyik pas sepertiga akhir. Bab terbaik saat penyingkapan ketika si pengoceh, seorang mahasiswa dengan riwayat keluarga Yahudi (bangsa pengelana), pergi ke hutan Amazon di masa “generasi bunga”, lalu terpikat pada satu suku di sana, bergumul dengan mereka, menjadi pendengar, dan menjalani perilaku khas dari suku tersebut yang meninggalkan apa yang kita sebut “kediaman yang tetap”; komunitas kecil yang marjinal ini terus berjalan, nomaden, sebab jika berdiam terlampau lama, matahari akan jatuh, terjadilah kekacauan, bencana, sebuah kiamat. Vargas Llosa membangun dua jalur cerita, selang-seling, yang pertama bab si ‘aku’—katakanlah Vargas Llosa sendiri—yang penasaran pada Saúl Zuratas, si mahasiswa etnologi itu yang jadi karibnya di kampus, atas sebab-sebab ia mengalami “pencerahan” atau “kelahiran baru” dari orang kota menjadi “mualaf Machiguenga, dan lantas jadi pengoceh.” Cerita kedua soal kisah Machiguenga sendiri, menuturkan kosmos dan kebudayaan mereka, dongeng, bualan, fiksi, gosip, dan lelucon mereka. Ada pertaruhan: dua narator yang harus berbeda—dan kita mendapatinya. Narator Vargas Llosa sangat tertata bahasanya; narator soal dongeng Machiguenga berisi seperti racauan, igauan, atau seperti judul novelnya: mengoceh tiada henti. Dalam keluarga-keluarga kecil Machiguenga yang berdiaspora di hutan Amazonia, peran si pengoceh menjadi sentral dari kosmos kehidupan mereka sebagai pengabar, mengikat dan menata jati diri plus perasaan manunggal akan komunitas senasib-sepenanggungan yang tercerai-berai.
Apa yang bikin novel ini mendatangkan banyak kajian adalah komentar-komentar politiknya soal peran keilmuan yang membawa misi “pengetahuan” sekaligus relasi parasitnya terhadap subjek riset yang seringkali membawa misi “pembaratan.” Saúl adalah pribadi yang secara intelektual menentang kampusnya (dan di belakangnya proyek-proyek kajian) untuk menundukkan Machiguenga dengan dalih “pemberadaban” untuk berdiam di satu tempat, tidak lagi berpencar, sebab secara inheren melawan jagat moral dan mitos suku tersebut. Apa yang terjadi pada mereka, sebagaimana komunitas-komunitas lain yang mendiami Amazonia, yang kita baca dari literatur-literatur soal lingkungan, adalah perkembangan keterdesakan yang meminggirkan, mula-mula lewat penaklukan pasukan Inca, lalu penjelajah, kaum misionaris dan bangsa Spanyol, cukong-cukong komoditas hutan, dan demam emas. Disusul kemudian penetrasi dari maskapai-maskapai pertambangan multinasional, perdagangan kokain, lalu pemberontakan (kaum gerilyawan dan atau narko-gerilyawan), dan apa yang belakangan jadi nomenklatur politik global: terorisme dan kontra-terorisme. Secara tidak langsung, saya teringat atas apa yang terjadi pada komunitas suku di Jambi, di Borneo, atau bangsa Papua di Papua Barat, dan komunitas-komunitas lebih kecil di hutan-hutan di Jawa. Novel ini, dengan sendirinya, menantang secara pemikiran.
Vargas Llosa juga memakai pendekatan analogi, dunia paralel, atas dunia minor Saúl dan dunia bangsanya. Mesin analogi ini bekerja dengan membandingkan, atau menautkan, nasib komunitas Machiguenga dan bangsa Yahudi (dalam istilah di novel ini “Yahwe-Tasurinchi”) yang terus berjalan, berpindah-pindah, berpencar ke seluruh dunia, memanggul nasib sebagai orang dan masyarakat yang kerap disalahkan, dikambinghitamkan, biang keladi dan mendapat cap pelbagai stigma, apabila terjadi kemalangan, bencana, atas nasib buruk orang lain. (Dalam kasus di Indonesia dijatuhkan pada “orang Tionghoa” dan “PKI”.) Paralelisme lain adalah sosok Saúl Zuratas sendiri, yang punya tanda lahir berupa tompel besar di sebagian wajahnya, sehingga dipanggil “Mascarita” (Muka Tompel), yang membuatnya “jadi marjinal di antara yang marjinal,” terus disepelekan dan diejek oleh “orang dan masyarakat normal”, betapapun Saúl adalah pribadi yang pasivis dan panjang akal. Noda ungu tua raksasa ini, bagi Saúl yang meyakini satu-satunya pahlawan literatur di dunia adalah Franz Kafka, dibandingkan sebagaimana nasib Gregor Samsa yang mendadak, ketika bangun di satu pagi, menjadi seekor serangga raksasa. Kisah Saúl karena tompelnya ini (dalam novel disebut “Gregor-Tasurinchi”), yang bikin ia dikucilkan dan bikin malu orang dan perasaan rendah diri yang menggerogoti jiwanya, disebut sebagai “kesurupan jelek,” sebelum kemudian ia pelan-pelan mengatasinya (atau sadar dari kesurupan) dan bahkan ia bisa membuat lelucon atasnya.
Usai menamatkan, dan mengantongi motif cerita yang sudah agak dikenali, saya membuka lagi bab awal novel Sang Pengoceh, dengan membawa pertanyaan: Apa arti tompel dari sebagian muka Saúl untuk kita, sebagai warga negara-bangsa, yang dari seorang pribadi tak sempurna ini pada akhirnya bikin dia, secara transformatif, menanggalkan kehidupan lamanya, menutupi jejak masa lalunya, dan lantas menjadi sosok yang sepenuhnya baru sebagai si pengoceh?
Saya teringat perjalanan-perjalanan singkat saya di luar Jawa, tetapi yang terus saya ingat adalah perjalanan pertama saya ke selatan Papua, tiga atau empat tahun lalu. Di sana saya bertemu dengan orang-orang dari keluarga-keluarga yang meninggalkan kampungnya, untuk “turun ke Merauke” ketika tanah-tanah mereka, yang semula hanya dikenali lewat kepemilikan bersama dengan patokan faam, dipaksa untuk dicacah, dibelah-belah, diberi garis batas oleh “orang-orang perusahaan” yang membawa kantong-kantong uang, dan tanah-tanah itu diambil sebagai lahan-lahan perkebunan dan pertanian raksasa demi apa yang disebut oleh janji pemerintah Indonesia saat itu “lumbung pangan, yang akan memberi makan rakyat Indonesia, kemudian dunia.” Bagaimana nasib para faam ini sekarang? Satu sore itu, ketika saya mengobrol dengan para bapak di halaman rumah tempat mereka menumpang sementara di kota Merauke, meninggalkan istri dan anak, untuk menuntut hak tanah (dan konsesi uang yang dibayar tidak sesuai janji), mengisahkan bagaimana “orang-orang perusahaan” ini, dengan bahasa yang terdengar rapi dan santun, berkata muluk-muluk hanya untuk akhirnya mendapati mereka mewakili “abu nawas tinggi”: sang penipu ulung.
Dalam kehidupan kita, barangkali, sejak lahir kita membawa “tompel Saúl”: pertanyaan yang mengusik secara moral maupun posisi dan pandangan politik kita terhadap peran kita secara tidak langsung telah mengusir dan meminggirkan “suku-suku adat” di sepanjang hutan-hutan dunia. Peran yang sama, barangkali, ketika kita melihat kemelaratan yang mencolok, pemiskinan luar biasa, tapi kita tidak tahu harus berbuat apa, atau kalaupun bisa bertindak, efek dan jangkauannya sangat terbatas.
Dalam novel Sang Pengoceh, sang seripigari—seorang tabib—berkata kepada Saúl: “Lahir dengan wajah sepertimu bukanlah kejahatan terburuk; kejahatan terburuk adalah tidak menyadari kewajiban.”●